Oleh: Arifin Al Bantani
Dalam beberapa dekade terakhir, istilah ekonomi Islam semakin sering terdengar. Bank syariah tumbuh, produk halal menjamur, dan label “syariah” menjadi identitas ekonomi yang tampak religius. Namun, di balik perkembangan itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah yang kita jalankan hari ini benar-benar ekonomi Islam, atau sekadar adaptasi simbolik dari sistem kapitalisme modern?
Ekonomi Islam sejatinya bukan sekadar soal larangan riba atau penggantian istilah bunga menjadi margin. Ia adalah sebuah sistem nilai yang utuh, yang bertujuan menciptakan keadilan distribusi, keseimbangan sosial, dan keberpihakan pada kemaslahatan umat. Ketika tujuan ini tidak tercapai, maka yang terjadi bukanlah penerapan ekonomi Islam, melainkan “islamisasi” kosmetik atas sistem ekonomi yang pada dasarnya eksploitatif.
Distorsi dalam Praktik Ekonomi “Syariah”
Dalam praktik perbankan modern, termasuk yang berlabel syariah, dana masyarakat yang mayoritas berasal dari umat Islam, dihimpun dan dikelola dalam skema besar korporasi. Secara makro, dana ini sering kali mengalir ke sektor-sektor padat modal yang dikuasai segelintir elite ekonomi. Akibatnya, terjadi paradoks: umat Islam menjadi penyedia dana terbesar, tetapi tidak menjadi penerima manfaat utama dari pertumbuhan ekonomi tersebut.
Sistem ini menciptakan ilusi kesejahteraan. Secara nominal, saldo tabungan nasabah bertambah. Namun secara riil, daya beli dan posisi ekonomi mereka tidak banyak berubah. Inflasi, ketimpangan akses modal, dan konsentrasi kekayaan tetap berlangsung. Di sinilah ekonomi Islam kehilangan ruhnya, karena ia seharusnya menolak akumulasi kekayaan pada segelintir pihak dan mendorong perputaran harta secara adil di tengah masyarakat.
Fondasi Ekonomi Islam: Keadilan, Bukan Sekadar Legalitas
Al-Qur’an menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam menempatkan distribusi sebagai isu sentral, bukan sekadar efisiensi atau pertumbuhan. Sistem ekonomi Islam menuntut keberpihakan struktural kepada kelompok lemah seperti petani kecil, pedagang mikro, buruh, dan masyarakat miskin.
Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan pelengkap, melainkan pilar utama. Dalam sejarah Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang efektif, bahkan mampu menghapus kemiskinan struktural pada masa tertentu. Namun hari ini, zakat sering diposisikan sebagai amal individual, bukan kebijakan ekonomi publik yang terintegrasi.
Kritik terhadap Kapitalisme yang Berlabel Islami
Kapitalisme modern bertumpu pada akumulasi modal, ekspansi tanpa batas, dan orientasi laba. Ketika sistem ini diadopsi tanpa kritik, lalu diberi label syariah, maka yang lahir adalah kontradiksi. Ekonomi Islam tidak netral secara moral; ia menolak eksploitasi, spekulasi berlebihan, dan ketimpangan ekstrem.
Kembali ke ekonomi Islam yang sebenarnya berarti berani mengkritik struktur ekonomi yang timpang, meskipun struktur itu dibungkus dengan istilah-istilah religius. Ini juga berarti menolak anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi otomatis menciptakan keadilan sosial. Dalam perspektif Islam, keadilan bukan efek samping, melainkan tujuan utama.
Jalan Kembali: Dari Simbol ke Substansi
Kembali ke ekonomi Islam yang sejati membutuhkan perubahan paradigma. Pertama, ekonomi harus dipandang sebagai sarana ibadah dan pengabdian sosial, bukan sekadar aktivitas mencari keuntungan. Kedua, kebijakan ekonomi harus diarahkan pada pemberdayaan umat, bukan hanya stabilitas sektor keuangan. Ketiga, institusi ekonomi Islam harus berani keluar dari logika kapitalisme arus utama dan membangun model yang berbasis komunitas, sektor riil, dan keadilan sosial.
Ekonomi Islam bukan nostalgia romantis masa lalu, tetapi tawaran alternatif bagi masa depan. Di tengah krisis global, ketimpangan ekstrem, dan dehumanisasi ekonomi, nilai-nilai Islam justru semakin relevan. Namun relevansi itu hanya akan nyata jika kita berani kembali ke substansinya, bukan berhenti pada simbol dan label.
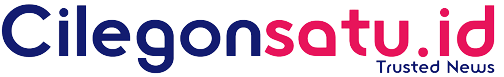






Tinggalkan Balasan